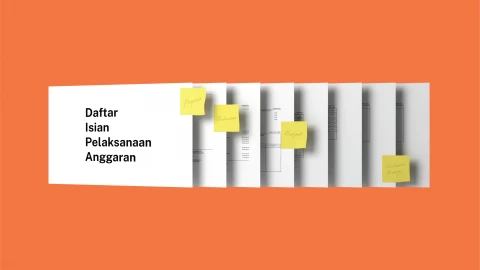G20 Dukung Implementasi Solusi Dua Pilar Untuk Keadilan Perpajakan Global

Negara-negara anggota G20 bersepakat untuk terus mendukung upaya implementasi Solusi Dua Pilar perpajakan internasional yang dinilai bersejarah dalam merombak arsitektur perpajakan internasional. Komitmen tersebut dinyatakan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral/Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) ke-3 G20 Presidensi Indonesia yang dilangsungkan pada 15-16 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali.
Reformasi sistem perpajakan internasional yang lebih adil menjadi salah satu fokus agenda lanjutan G20 yang dikedepankan oleh Presidensi G20 Indonesia. Reformasi sistem perpajakan internasional tersebut dilakukan melalui pengalokasian hak pemajakan ke negara yang menjadi pasar produk barang dan jasa digital (negara pasar) yang dikenal sebagai Pilar 1. Serta memastikan bahwa semua perusahaan multinasional (multinational enterprise /MNE) membayar pajak minimum di semua tempat perusahaan tersebut beroperasi atau yang disebut dengan Pilar 2.
Pada Oktober 2021, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mensahkan Solusi Dua Pilar dan detail rencana implementasinya yang dinilai cukup ambisius yaitu untuk menerapkan peraturan baru mengenai pemajakan pada tahun 2023.
Sementara sejak November 2021, tercatat 137 negara anggota OECD/G20 Inclusive Framework (IF), yang mewakili lebih dari 90 persen produk domestik bruto (PDB) global, termasuk Indonesia, telah menyetujui Solusi Dua Pilar. Meski demikian, untuk mewujudkan kedua pilar ini menjadi landasan hukum yang konkret, perlu disusun suatu Konvensi Multilateral (Multilateral Convention/MLC). Karena itu, kepemimpinan Indonesia pada forum G20 2022 menjadi krusial dalam mengawal kemajuan rencana implementasi Solusi Dua Pilar tersebut.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan solusi dua pilar akan menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil.
“Konsensus global atas konsep tersebut akan menjadi kunci bagi otoritas pajak dalam melakukan pemajakan atas transaksi lintas batas berbasis digital serta menangani masalah penghindaran pajak,” ucap Yon.
Sementara Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra mengatakan kesepakatan Solusi Dua Pilar mencapai perkembangan penting dalam pertemuan FMCBG ke-3 tersebut.
Meskipun penandatanganan Konvensi Multilateral (Multilateral Convention/MLC) Pilar 1 diundur ke pertengahan tahun 2023 dan ditargetkan mulai berlaku (entry into force) pada tahun 2024 mendatang, mengingat masih tingginya dinamika perumusan skema pemajakan pada Pilar I tersebut, namun terdapat kemajuan signifikan dalam penyusunan ketentuan teknis tentang hak pemajakan baru bagi yurisdiksi pasar.
“Jadi kita akan upayakan progress-nya as much as possible dalam Presidensi G20 Indonesia dan juga nanti akan terus mendorong pada Presidensi G20 India (di 2023),” ungkap Wempi.
Tak hanya itu, telah tercapai pula kesepakatan mengenai model rules untuk Pilar 2. Model rules merupakan dokumen panduan bagi masing-masing negara yang akan menerapkan Pilar 2. Negara yang akan menerapkan Pilar 2, nantinya harus meratifikasi aturan domestik mengacu pada model rules tersebut. Pajak korporasi minimum global ini diharapkan mulai dikenakan pada 2023.
Kabar istimewa lainnya dari agenda perpajakan internasional pada perhelatan FMCBG ke-3 G20 yaitu tercapainya komitmen bersama sebelas negara di kawasan Asia untuk memperkuat pertukaran informasi (Exchange of Information) sebagai upaya memerangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Komitmen tersebut dituangkan dalam Asia Initiative Bali Declaration yang ditandatangani pada 15 Juli 2022 oleh Brunei Darussalam, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Makau, Singapura, dan Thailand.

Mengganti yang telah usang
Aktivitas ekonomi lintas yurisdiksi turut terdisrupsi dalam era digitalisasi. Sistem pajak internasional yang selama ini berlaku tidak lagi memadai untuk mengakomodasi pemajakan internasional atas model bisnis yang telah bergeser dengan pesat seiring perkembangan teknologi. Risiko meningkatnya praktik penghindaran pajak pun menjadi tak terelakkan.
Partner, DDTC Fiscal Research & Advisory Bawono Kristiaji atau kerap disapa Aji memaparkan beberapa contoh sistem pajak internasional yang sudah tidak relevan. Misalnya sistem pajak internasional saat ini masih merujuk pada separate entity approach atau separate accounting approach. Alhasil, perusahaan multinasional yang sebenarnya adalah entitas global, malah entitasnya dilihat secara terpisah-pisah per negara. Hal ini membuat setiap otoritas pajak kesulitan melihat gambaran dari suatu perusahaan multinasional.
Persoalan lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai hak pemajakan yang masih berbasis kehadiran fisik. Tidak ada alokasi pajak untuk negara pasar tanpa adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sehingga negara pasar sebagai yurisdiksi sumber bagi perusahaan berbasis digital misalnya, tidak dapat memungut pajak penghasilan kepada perusahaan tersebut karena tidak adanya kehadiran fisik (BUT) dari perusahaan tersebut di negara pasar.
Tak hanya itu, isu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) atau penggerusan basis pajak dan pengalihan laba juga menjadi tantangan tersendiri dalam perpajakan internasional karena semakin marak terjadi di tengah laju globalisasi dan digitalisasi ekonomi.
Aji mengatakan meskipun setiap negara sudah memiliki anti avoidance rules atau ketentuan anti penghindaran pajak, namun belum ada koherensi antarnegara mengenai ketentuan tersebut. Hal ini tak jarang memicu praktik aggressive tax planning oleh pelaku usaha khususnya perusahaan multinasional. Mereka memanfaatkan celah-celah yang timbul akibat interaksi pajak antarnegara ketika melakukan aktivitas ekonomi lintas yurisdiksi.
Dikutip dari OECD, BEPS merupakan strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
Bagi negara berkembang yang rata-rata 80 persen pendapatan negaranya berasal dari penerimaan pajak, tentunya BEPS atau praktik penghindaran pajak akan sangat merugikan karena berdampak pada terhambatnya pembangunan di negara tersebut.
Potensi hilangnya penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) Badan global setiap tahunnya akibat penghindaran pajak cukup besar nilainya yakni sebesar USD100-240 miliar berdasarkan estimasi OECD. Bahkan IMF memprediksi lebih besar lagi yaitu senilai USD600 miliar. Angka tersebut akan terus bertambah mengikuti jumlah transaksi bisnis yang juga semakin berkembang.
Agar memperoleh solusi efektif maka seluruh masalah perpajakan internasional tersebut memerlukan penanganan secara global.
“Karena ini persoalan global lebih baik memang solusinya bersifat multilateral dibanding unilateral atau domestic action, karena bisa menciptakan pajak berganda, ketidakpastian, sekaligus mendistorsi ekonomi global,” ungkap Aji.
Solusi Dua Pilar
Yon Arsal mengungkapkan Solusi Dua Pilar yang diinisiasi OECD/G-20 Inclusive Framework (IF) akan memainkan peran penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan serta diharapkan mampu memperkuat kerangka perpajakan internasional dalam menghadapi model bisnis baru yang terus berkembang.
Pilar 1 bersifat wajib atau harus diterapkan (minimum standar) oleh anggota OECD/G20 IF yang sudah menyepakati Solusi Dua Pilar. Sedangkan Pilar 2 bersifat common approach (tidak wajib). Meski demikian akan tetap tunduk jika negara lain yang berhubungan dengan bisnis perusahaan multinasional tersebut menerapkan Pilar 2.
Adapun Pilar 1 mensyaratkan tiap negara untuk membatalkan kebijakan pajak digital yang bersifat unilateral, seperti halnya digital services tax yang contohnya diterapkan oleh India, UK, Perancis, ketika skema Pilar I telah diimplementasikan.
Pilar 1 yakni Unified Approach, merupakan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik, tetapi lebih kepada kehadiran ekonomi signifikan. Pendekatan ini berlaku bagi perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto global di atas EUR20 miliar dan profitability (laba sebelum pajak terhadap penghasilan bruto) di atas 10 persen dengan pengecualian untuk bisnis ekstraktif dan jasa finansial yang teregulasi.
Untuk teknis formula dasar, nantinya akan ada pengalokasian 25 persen keuntungan (residual profit) perusahaan multinasional ke negara pasar. Jumlah ini kemudian akan dibagikan kepada negara pasar berdasarkan porsi penjualannya di masing-masing negara pasar tersebut.
“Jadi Pilar Satu ini tidak ditujukan untuk mengatasi penghindaran pajak, tapi lebih ke pengembangan konsep baru terkait hak pemajakan beserta penentuan alokasinya untuk masing-masing negara atas bisnis atau ekonomi yang terdigitalisasi,” ujar Yon.
Sementara Pilar 2 merupakan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak. Pilar 2 terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR).
GloBE dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global sebesar 15 persen ditinjau dari negara domisili. Sedangkan STTR memberi kewenangan kepada negara sumber memberlakukan tarif withholding tax secara penuh tanpa reduced rate dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) apabila penerima penghasilan yang berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili.
Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (country-by-country reporting/CbCR) dokumentasi transfer pricing.
Yon mengatakan konsep ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan praktik penghindaran pajak untuk mengatasi penghindaran pajak ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low-tax jurisdictions).
“Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak akan dilakukan melalui mekanisme pertukaran informasi (exchange of information) sehingga otoritas pajak di Indonesia akan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisa terhadap laporan Wajib Pajak,” ucap Yon.
Senada, Aji menyampaikan dengan tarif pajak global minimum pada Pilar 2, tidak akan ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi.
“Nah ini tentunya bakal jadi game changer karena ini berupaya untuk mengurangi kompetisi pajak global. Kita tahu bahwa selama dua dekade terakhir itu tarif PPh badan rata-rata global itu turun hampir mencapai 8 persen. Jadi, memang ada fenomena race to the bottom. Sehingga dengan adanya income inclusion rule (penghasilan luar negeri ditarik ke negara domisili), ini akhirnya berupaya mau Anda berinvestasi di mana saja akan dikenakan tarif pajak atau beban pajaknya sama,” papar Aji.
Rinci mencermati
Solusi Dua Pilar menurut Aji merupakan kebijakan yang revolusioner karena sudah lebih berani mereformasi banyak aspek perpajakan internasional. Tidak hanya berupaya mencegah kompetisi pajak yang merugikan negara lain dan mengantisipasi perencanaan pajak yang agresif, tetapi juga membenahi keseluruhan lanskap pajak internasional untuk menjamin alokasi laba dan pajak yang lebih adil.
Namun, Aji mengingatkan tantangan-tantangan yang muncul dari aspek teknis yang perlu diperhatikan. Di Pilar 1 misalnya detail teknik cara penentuan suatu penghasilan yang berasal dari market yurisdiksi (revenue sourcing rules) masih belum jelas, apakah berdasarkan jumlah pengguna, jumlah transaksi di suatu negara, dan sebagainya.
“Karena ini yang akan menentukan seberapa banyak setiap negara itu akan mendapat kuenya. Jadi di sini juga tentunya alot dari sisi formula apa yang dipergunakan, tapi juga nanti ada tantangan mengenai bagaimana memastikan bahwa datanya semua transparan,” tutur Aji.
Masalah kelembagaan juga menurut Aji kemungkinan muncul setelah pilar 1 ditandatangani, dalam hal mekanisme pengawasan implementasi Pilar 1 secara global.
Selanjutnya, perubahan konsep pemajakan yang turut mengubah prinsip bentuk usaha tetap tidak lagi berbasis kehadiran fisik, akan berimplikasi pada lebih dari 3000 P3B (perjanjian penghindaran pajak berganda) yang harus diubah di seluruh dunia. Sebab itu, dibutuhkan skema konvensi multilateral.
Di samping itu, tantangan menurut Aji juga datang dari aspek tax certainty yaitu kepastian hukum apabila terjadi sengketa, mengingat penerapan Pilar I dapat berimplikasi pada adanya kemungkinan perusahaan multinasional dikenakan pajak berganda. Sehingga perlu diperjelas mekanisme penyelesaian sengketanya. Karena sepengamatan Aji, dari pengalaman-pengalaman arbitrase internasional cenderung lebih berpihak pada negara capital exporting countries, bukan negara-negara berkembang.
“Ini tentu lebih kompleks dan tantangannya memang bagaimana secara timeline kita bisa ideal atau ada konsensus terkait dengan aspek-aspek teknis tersebut,” ujar Aji.
Aji berharap Indonesia sebagai Presidensi G20 akan dapat terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam setiap detail pembahasan ketentuan Dua Pilar.
“Yang akhirnya kita bisa lakukan adalah bagaimana meningkatkan awareness dari setiap negara G20 bahwa apakah proposal, khususnya two pillars solution ini, benar-benar sesuatu yang melegakan untuk semua atau mayoritas,” saran Aji.
Menghitung untung
Skema Pilar 1 maupun Pilar 2 akan berimplikasi pada penerimaan pajak. Yon menerangkan melalui pengaturan mengenai alokasi hak pemajakan baru dalam komponen Pilar 1, maka Indonesia akan turut memperoleh alokasi hak pemajakan baru dari perusahaan-perusahaan digital yang selama ini telah beroperasi di Indonesia namun tidak dapat dipajaki dikarenakan tidak adanya kehadiran fisik dari perusahaan tersebut.
Yon melanjutkan, implementasi Pilar 2 memungkinkan Indonesia memperoleh potensi tambahan penerimaan pajak apabila terdapat subsidiary atau entitas anak grup perusahaan multinasional yang memiliki Entitas Induk Tertinggi (Ultimate Parent Entity) di Indonesia, melakukan kegiatan operasional di negara yang tidak mengenakan pajak atau menerapkan tarif pajak rendah.
“Potensi tambahan penerimaan pajak kedua Pilar masih dalam tahap penghitungan dan proses analisis lebih lanjut karena pembahasan detil implementasi kedua Pilar masih berlangsung di tingkat teknis di forum internasional (OECD),” ungkap Yon.
Sementara, berdasarkan kajian ekonomi yang dilakukan OECD, melalui implementasi Pilar 1 yang menjanjikan sistem pajak internasional yang lebih adil terdapat tambahan sebesar USD125 miliar setiap tahunnya yang dapat dialokasikan ke negara pasar.
Menilik kajian tersebut, Aji menerangkan yang perlu dicermati bahwa Pilar 1 hanya untuk perusahaan multinasional dengan threshold di atas EUR20 miliar -yang kemungkinan jumlahnya tidak lebih dari 150 perusahaan di seluruh dunia-. Dengan demikian, hanya sedikit perusahaan multinasional yang nantinya akan harus tunduk pada ketentuan Pilar 1 tersebut.
Lebih dari itu, perlu diperhatikan pula formula penghitungan alokasi yang dipakai. Dari residual profit perusahaan multinasional di atas 10 persen laba global yang diperuntukan alokasi ke negara pasar, ternyata juga masih dialokasikan lagi dan hanya sekitar 25 persen saja yang akan diterima oleh negara berkembang.
Menurut Aji, dari kalkulasi yang dilakukan oleh akademisi global, dampak Pilar 1 terhadap penerimaan pajak negara berkembang tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak rendah.
“Jadi, penting bagi kita sebagai Presidensi G20 untuk menyuarakan apa yang perlu didalami dan direvisi dari skema (Pilar 1) tersebut, mumpung belum terlambat,” ungkap Aji.
Sementara, dengan pengenaan pajak minimum melalui Pilar 2, diestimasi terdapat tambahan PPh global hingga 4 persen atau sekitar USD150 miliar per tahun.
Aji mengemukakan dampak Pilar 2 terhadap penerimaan pajak negara berkembang juga diprediksi sedang-sedang saja.
“Karena tarif pajak efektif minimumnya itu kan dilihat dari negara domisili, jadi ini bias kepada negara-negara capital exporting. Bisa jadi negara-negara capital exporting yang akan mengenakan top up tax dari subsidiaries dia di berbagai negara karena investornya kan kebanyakan dari negara tersebut,” beber Aji.
Di samping itu, dari segi teknis, Aji berpendapat skema STTR pada Pilar 2 memerlukan pembahasan yang lebih memadai karena di dalamnya terkandung hak-hak negara sumber yang harus diperjuangkan.
Di lain sisi, hal menarik lainnya, Aji mengatakan dengan adanya tarif pajak minimum, Indonesia juga perlu meninjau ulang rezim fasilitas pajak yang diberikan kepada perusahaan multinasional. Sebab, kalaupun mengenakan tarif pajak lebih rendah dari tarif minimum 15 persen, negara lain akan mengenakan pajak tambahan hingga mencapai tarif minimum tersebut.
Namun, dengan diperkenalkannya pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum top up tax di bawah Pilar 2 pada awal tahun ini, menurut Aji setidaknya akan menjamin negara berkembang mendapat hak pemajakan pertama atau terpenuhinya tarif minimum 15 persen.
“Ini semua adalah pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan tersebut nantinya akan mempengaruhi seberapa besar kita bisa mendapatkan additional revenue,” pungkas Aji.