Lahir di Sawah, Tak Menyerah Gapai Cita

Setiap sore, saat remaja, Sumarlin mengasuh dua sepupu ciliknya di Taman Suropati. Ia tak menyadari bahwa kelak, dia menjadi menteri di beberapa gedung megah, tak jauh dari taman tersebut.
Kisah hidup Menteri Keuangan Republik Indonesia Kabinet Pembangunan V periode 1988-1993, ini termasuk fenomenal. Kelahirannya saja di tempat yang tak biasa. Yaitu, di tengah sawah, saat sang ibunda, Karmilah, yang sedang bekerja di antara tanaman padi yang sudah menguning itu, tiba-tiba saja merasakan perutnya sakit.
Ya, Ahad, 7 Desember 1932, Legi, di tengah sawah di Desa Ngadirejo, suasana tiba-tiba gaduh tak seperti biasanya. Putri Toedjo Towinangoen, pemilik sawah tersebut, tiba-tiba saja melahirkan bayinya di area persawahan yang berada di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur itu. Sang bayi kemudian diberi nama Katoebin yang artinya lahir di sawah pada hari Minggu. Proses kelahiran dibantu Mbah Boerhan, seorang pemuka agama yang kebetulan lewat. Bayi laki-laki inilah yang kelak dikenal sebagai sosok yang ikut menentukan nasib ekonomi di negeri ini, begawan ekonomi Indonesia.

Selang tiga tahun, nama Katoebin diganti. Menurut putera ketiga Sumarlin, Antonius Widyatma, alasannya sering sakit. Dan setelah dibawa ke orang pintar, nama cucu kakek Toedjo Towinangoen ini harus diganti dengan yang berbau perempuan. Akhirnya Katoebin diganti Sumarlin. Masa kecil sosok yang kelak dibaptis dengan nama Johannes Baptista (JB) Sumarlin, ini tak lepas dari pengawasan sang kakek yang dikenal sebagai orang berada di desa tersebut. Selain sawah yang luas, ada juga sebidang hutan jati di sisi aliran Sungai Lahar di kawasan tempat Gunung Kelud bertengger.
Bintang Kelas
Meski bukan cucu pertama, Sumarlin mendapat perhatian dari sang kakek. Namun, masa kecil Sumarlin tak lantas semulus jalan tol. Banyak kerikil dan aral melintang. Tapi, bukan JB Sumarlin namanya jika tak mampu melewati itu semua.
Sumarlin terpaksa melewati masa kecilnya tanpa kasih orang tua secara utuh. Ini terjadi ketika sang ayah, Sapoean Pawirodikromo alias Kasan Pawiro bercerai dengan sang ibu ketika dirinya berusia lima tahun.
Sesekali, Sumarlin kecil bertandang ke desa sebelah, tempat ayahnya bermukim. Sang ayah kadang membekalinya uang. Dari bekal itu, Sumarlin bisa membeli jajanan lokal kesukaannya, tiwul singkong dan pecel sayur. Tiwul ini sampai akhir usianya masih sering dikudap Sumarlin. Saking sukanya, kadang konsumsinya berlebih, kisah Anton --sapaan Antonius yang tinggal satu atap bersama sang ayah di akhir masa tuanya itu.
Hidup jauh dari ayah membuatnya tidak kolokan. Sumarlin kecil selalu ikut sang ibu ke sawah dan turut membantu pekerjaan sang ibu. Itu karena ibunda Sumarlin adalah seorang buta huruf, hanya bisa menjadi buruh di sawah milik kakeknya. Terlebih, di masa itu, kodrat perempuan masih terbelenggu dengan "dapur, sumur, kasur". Bagi keluarga petani, selain mengemban "kodrat" itu, anak perempuan harus ikut ke sawah atau kebun setiap hari. Tak perlu sekolah. Tak terkecuali sang ibu, Karmilah. Anak laki-lakilah yang diutamakan mengenyam pendidikan. Karenanya, Sumarlin tak menyia-nyiakan keputusan sang kakek mengirimnya ke sekolah desa atau volkschool.
Di Blitar, Sumarlin selalu menjadi juara kelas. Lulusan terbaik dari volkschool di Jatimalang, juga di vervolgschool Desa Sentul. Bahkan, sang Kepala Sekolah Adi Dirdjomajono, memilih Sumarlin yang kala itu berusia 10 tahun, sebagai satu-satunya anak Desa Ngadirejo yang bisa meneruskan ke vervolgschol Desa Sananwetan, saat sistem pendidikan Belanda beralih ke sistem pendidikan Jepang pada 1942. Seperti anak kecil lainnya, saat senggangnya Sumarlin juga hobi permainan sepak bola tanpa alas kaki bersama teman-teman.
Di malam hari, Sumarlin beranjak ke amben sang kakek. Bukan cuma tidur melepas lelah, tapi sang cucu ini selalu menantikan wejangan sang kakek menjelang tidur. Bahasa Kakek Toedjo yang sederhana membuat Sumarlin paham betul bagaimana harus berlaku dan bersikap untuk hidup. Salah satu wejangan sang kakek adalah, aja adigang adigung adiguna, jangan sok besar, sok hebat, sok jagoan.
Menurut pengakuan Sumarlin dalam Buku Cabe Rawit yang Lahir di Sawah, karya Bondan Winarno, 2012, amben itu adalah moment of truth. Percakapannya dengan sang kakek di pembaringan dari anyaman bambu itu, mengubah pendiriannya untuk membahagiakan sang ibu, tidak manja dan lebih giat belajar.
Wejangan lain yang amat melekat pada Sumarlin adalah tentang pentingnya sekolah. “Kalau tak sekolah, kamu mau jadi apa? Lihat pamanmu! Dia bisa jadi pejabat karena sekolahnya tinggi…,” kutip Bondan dalam bukunya itu.
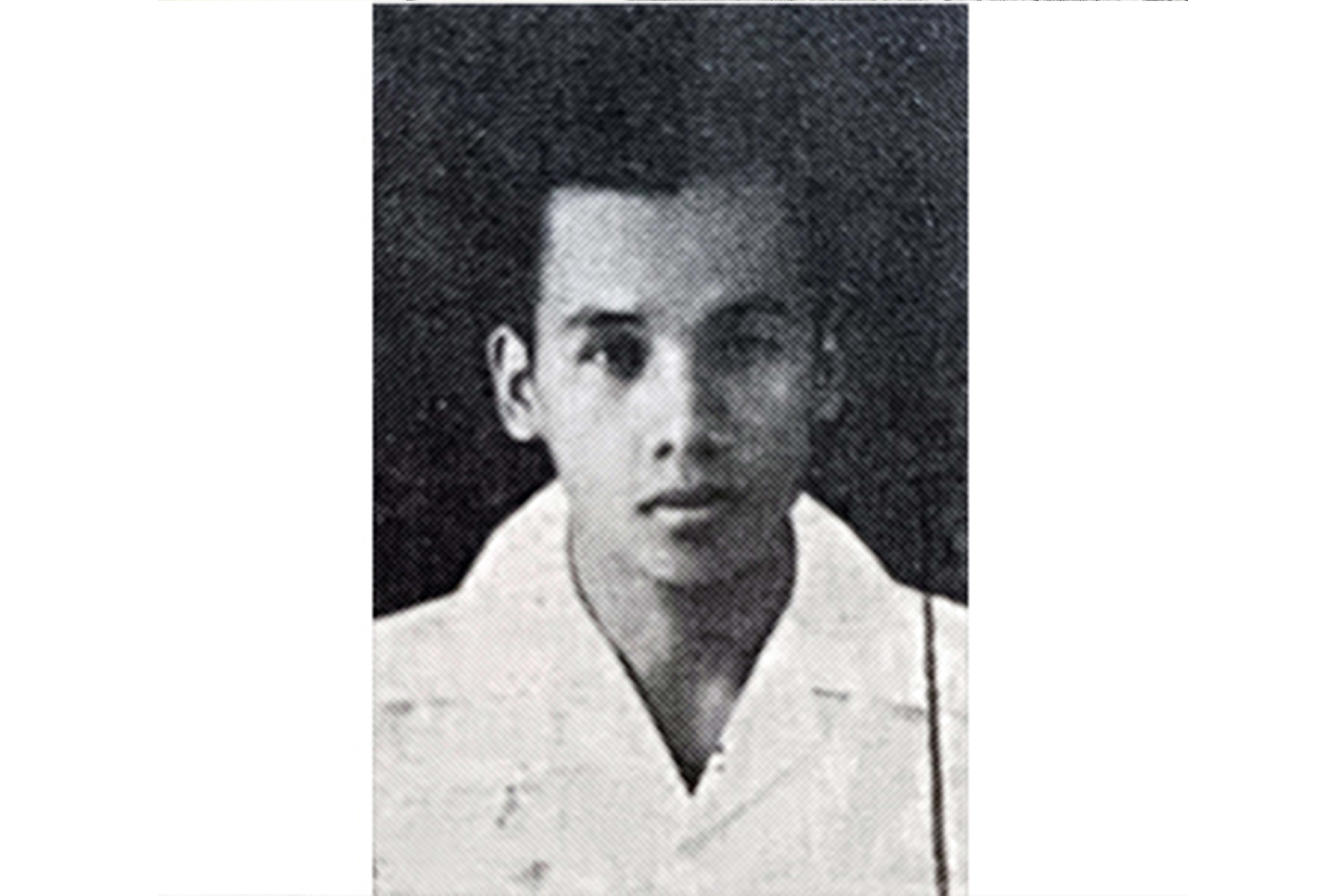
Menumpang Hidup demi Sekolah
Bersama sang ibu, ia tinggal di rumah sang kakek. Tapi lama kelamaan, penghuni rumah itu semakin bertambah. Apalagi, sang ibu juga kemudian memiliki anak dari pernikahan berikutnya. Rumah sang kakek pun semakin sesak dengan banyak anak baru yang muncul. Saat itulah sang paman yang tentara diminta sang kakek menjemput Sumarlin yang sudah tamat vervolgschol. Sumarlin kemudian tinggal dengan sang paman, Moekidjam, dan keluarganya di Kediri.
Episode kehidupannya di Kediri dijalani layaknya anak yang ngenger alias menumpang. Sumarlin harus turut mengerjakan pekerjaan rumah di kediaman paman agar dapat terus bersekolah, ungkap Anton. Dari Kediri, episode hidupnya beralih ke Yogyakarta mengikuti kepindahan sang paman. Karena dalam suasana perang Kemerdekaan, Sumarlin terpaksa putus sekolah. Di sinilah, Sumarlin belajar tentang pendidikan bergerilya. Atas petunjuk sang paman juga, akhirnya Sumarlin ikut bela negara sebagai tentara pelajar.
Pada 1949, akhir Desember, Pasca Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu, Sumarlin harus membuat keputusan besar. Dalam buku Cabe Rawit yang Lahir di Sawah, Sumarlin sendiri mengakui sempat terpengaruh oleh keputusan teman-temannya yang terus mengabdi di jalur militer.
“Tapi saya menyadari bahwa saya tak punya ‘potongan’ menjadi tentara, saya juga tidak berbakat menjadi tentara karena tidak tahan melihat kekerasan,” katanya begitu antara lain ia menyebutkan alasannya. Sumarlin pun memutuskan kembali ke bangku kelas dua Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. Dan pada 1951 mengikuti sang paman pindah ke Jakarta dan melanjutkan sekolah di ibu kota negara ini.
Di Jakarta, Sumarlin bersama sang Paman tinggal di Jalan Besuki 23, Menteng, Jakarta Selatan. Setiap sore, ia mengasuh dua sepupunya yang masih kecil di Taman Suropati. Sosok yang melanjutkan sekolahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar master dari Universitas Berkeley Amerika Serikat, serta gelar doktor di Universitas Pittsburgh ini tak menyadari bahwa kelak, dia akan berkantor di beberapa gedung megah, tak jauh dari taman itu. Tak sekadar berkantor di gedung megah tersebut, melainkan 15 tahun sebagai Menteri.
Bahkan, Pemimpin Redaksi Euromoney Neil Osborn menyebut bahwa sosok yang kemudian meraih gelar profesor ini adalah satu-satunya menteri keuangan di dunia yang berhasil mengubah struktur ekonomi di negaranya. Osborn menyampaikan pendapatnya tersebut, saat memberikan penghargaan dari lembaganya yang terpandang di dunia itu, kepada Sumarlin sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Dunia pada 1989.







